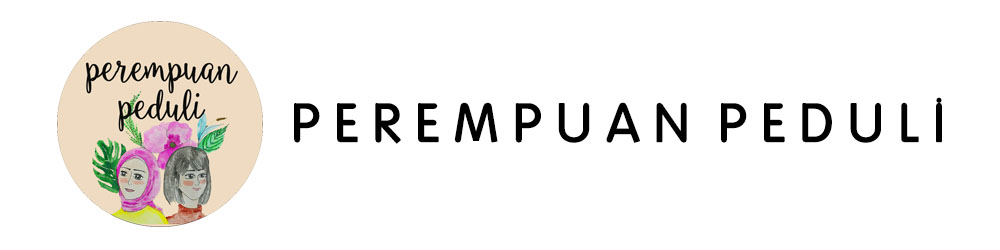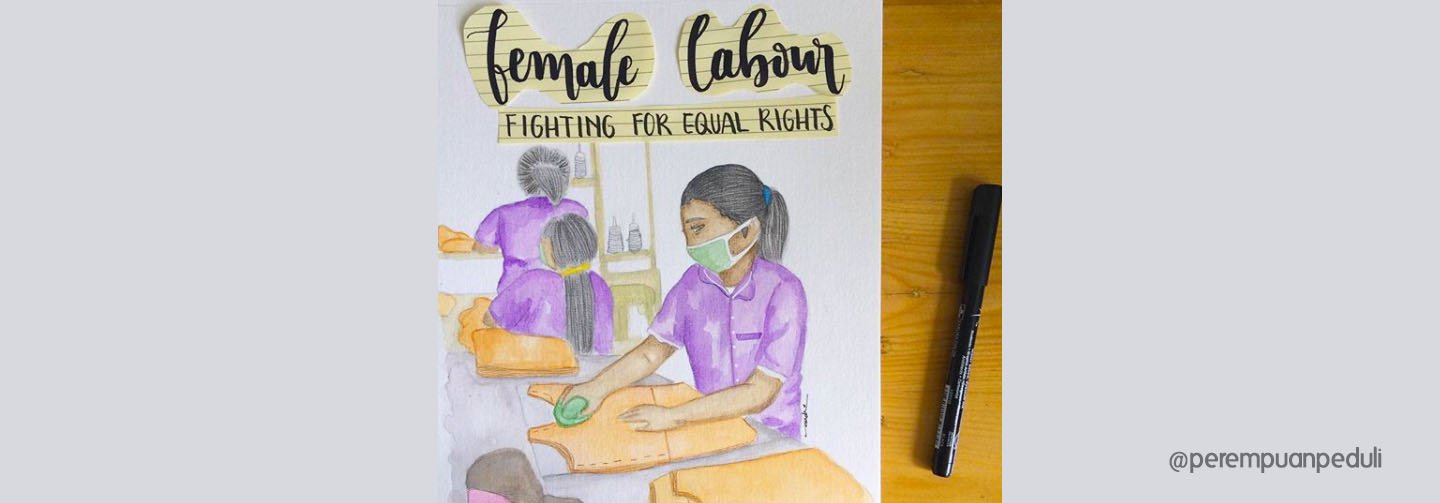Meninjau Feminisme Marxis: Perempuan dan Kerja
Razali Ritonga dalam laporannya berjudul “Kebutuhan Data Ketenagakerjaan untuk Pembangunan Berkelanjutan” memaparkan berbagai poin penting terkait ketenagakerjaan berdasarkan jenis kelamin. Data rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja (employment to population ratio) tahun 2014 menyebutkan, laki-laki memiliki persentase kesempatan kerja sebesar 78,27% sedangkan perempuan hanya 47,08% saja. Pada data tingkat pekerja berupah rendah tahun 2013, persentase laki-laki yakni 28,37% sementara perempuan memiliki persentase sebesar 36,15%. Artinya, perempuan diberikan upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sementara pada data tingkat kesenjangan upah gender (Gender Wage Gap) tahun 2014 dipaparkan persentase sebesar 22,3%. Data ini menunjukkan, kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki masih tinggi. Upah laki-laki masih lebih tinggi 22,3% dibanding perempuan. Berdasarkan ketiga data tersebut, kita dapat melihat bahwa kesempatan kerja perempuan masih lebih rendah dari laki-laki dan kesenjangan upah perempuan terhadap laki-laki masih tinggi.
Berbicara tentang ketenagakerjaan, ILO Indonesia memaparkan data BPS bulan Agustus 2014 dan menyebutkan bahwa berdasarkan proporsi pekerja menurut pekerjaan, perempuan paling dominan bekerja di bidang pekerjaan profesional dan jasa serta bagian penjualan. Sementara berdasarkan angka absolut, perempuan lebih dominan bekerja sebagai buruh tani dan perikanan (12,5 juta), diikuti sektor jasa dan penjualan (12,3 juta). Dalam hal ini, jenis pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan dengan tingkat upah rata-rata terendah di Indonesia. Selain upah rendah tersebut, permasalahan lain berupa diskriminasi di tempat kerja acap kali dialami oleh perempuan. Berita online CNN Indonesia berjudul “Kisah Buruh Perempuan di Tempat Kerja” memberitakan, buruh perempuan mengalami berbagai penderitaan di tempat kerja. Beberapa di antaranya berupa upah rendah, beban yang berat tanpa memperhitungkan kondisi fisik sehingga pekerja mengalami keguguran, tidak adanya fasilitas ruang laktasi yang menyebabkan pekerja harus ke kamar mandi untuk memerah ASI, tidak adanya fasilitas kesehatan terhadap perempuan pasca keguguran (hanya disuruh beristirahat di tempat kerja selama beberapa jam kemudian diminta untuk kembali bekerja), tidak ada bantuan biaya melahirkan, fasilitas air minum yang tidak layak, hingga pemutusan kerja karena cuti melahirkan.
Dalam artikel Koalisi Perempuan Indonesia berjudul “Catatan Hitam Buruh Perempuan 2016” disebutkan buruh pabrik perempuan kehilangan hak maternity mulai dari hak cuti haid, melahirkan, dan laktasi. Hal lain yang menjadi masalah, yaitu jaminan upah minimal, fasilitas dalam bekerja, jaminan kesehatan, cuti buruh, dan asuransi (hanya laki-laki yang mendapatkan asuransi karena laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga dan buruh perempuan bukan kepala keluarga). Melihat permasalahan tersebut, beberapa pertanyaan yang muncul adalah: mengapa kesempatan kerja perempuan lebih rendah dan diskriminasi masih terjadi di tengah “emansipasi” yang digembar-gembor masyarakat masa kini? Bagaimana buruh perempuan dapat terlepas dari opresi?
Menurut feminisme Marxis, perbedaan fungsi dan status perempuan disebabkan oleh permasalahan kelas. Penindasan perempuan dapat terjadi pada produk politik, sosial, dan struktur ekonomi yang berkaitan erat dengan sistem kapitalisme (Arivia 111). Dalam hal ini, kapitalisme digambarkan sebagai hubungan transaksional yang pada dasarnya eksploitatif (Tong 142). Lebih lanjut, kapitalisme menyebarluaskan hubungan pertukaran dan pekerja merasa wajar apabila mendapatkan upah dengan menukarkan tenaganya (Arivia 113). Hubungan pertukaran yang eksploitatif ini makin kuat karena pihak yang berkuasa (pemilik modal) mempunyai monopoli terhadap alat produksinya, termasuk pekerja. Pemodal sudah tidak lagi melihat pekerja sebagai “manusia” melainkan “alat” untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya.
Mode produksi saat ini mengalami revolusi sepenuhnya yang juga secara bersamaan membuat revolusi terhadap tatanan sosial secara keseluruhan. Mode produksi saat ini semata-mata untuk mencapai keuntungan yang cepat dan berguna langsung (Engels 246). Dalam hal ini, pekerja tidak lagi utuh dan teralienasi dengan empat cara. Pertama, pekerja teralienasi dari produk kerja mereka; kedua, pekerja teralienasi dari diri mereka sendiri; ketiga, pekerja teralienasi dari manusia lain; keempat, pekerja teralienasi dari alam. Bagaimanapun, analisis kelas memang tidak dapat digunakan untuk menganalisis ketertindasan perempuan karena perempuan yang berasal dari ekonomi tinggi maupun rendah tetaplah teropresi. Kelas yang ada adalah kelas perempuan dan laki-laki, karena belenggu perempuan adalah dirinya yang bekerja pada bidang yang tidak menghasilkan komoditi seperti laki-laki. perempuan bekerja di bidang domestik dan tidak dianggap bernilai dan sebab itulah perempuan terus mengalami penindasan (Arivia 115).
Mengingat kapitalisme membuat pekerja menjadi teralienasi, Marxis ingin menghadirkan perempuan sebagai manusia yang utuh, terintegrasi, dan berbahagia (Tong 147). Marxisme menjanjikan manusia sebagia sosok yang bebas, perempuan dan laki-laki bersama membangun struktur sosial dan peran sosial yang memungkinkan kedua gender untuk merealisasikan potensi kemanusiaannya secara penuh (Tong 149). Berkaitan dengan hubungan kerja perempuan dan laki-laki, Engels dalam bukunya berjudul “The Origin of the Family, Private Property, and the State” menyebutkan, emansipasi perempuan dapat terjadi apabila perempuan dapat mengambil bagian dalam produksi sosial berskala luas dan tanggung jawab domestik tidak lagi menjadi tanggungan perempuan (204).
Lebih lanjut Engels mengungkapkan, seorang istri dapat diemansipasikan apabila perempuan mampu mandiri dengan masuk ke industri publik agar tidak bergantung dengan laki-laki (Tong 153). Benston juga memberikan solusi lain guna emansipasi perempuan, yaitu berupa sosialisasi pekerjaan rumah tangga serta pengasuhan anak (Tong 162). Selain masukan Engels dan Benston, feminis Marxis juga memberikan ide lain, yakni berupa comparable woth (nilai setara). Comparable worth ini fokus terhadap “poin nilai” dalam komponen pekerjaan, yaitu pengetahuan dan keahlian, tuntutan mental, pertanggungjawaban, dan kondisi kerja (Tong 165-166). Feminis Marxis sangat mendukung ide ini karena berkaitan dengan akses kemiskinan dan nilai kerja (Tong 166).
Mengaitkan kasus buruh perempuan dengan pemikiran feminisme Marxis, nampak jelas bahwa pekerja perempuan masuk dan terjerumus ke dalam arus kapitalisme. Buruh perempuan dianggap sebagai “alat” untuk menghasilkan komoditas. Mereka tidak lagi menjadi manusia yang utuh melainkan teralienasi dari dirinya sendiri dan berujung krisis psikologis. Perempuan hamil terpaksa terus bekerja meskipun dengan beban yang berat, perempuan menyusui harus bolak-balik ke toilet untuk memeras ASI karena tidak ada ruang laktasi, hingga harus menyumpal payudara dengan pembalut karena kondisi kerja yang mengharuskannya terus duduk. Apalagi saat sedang hamil dan akan melahirkan, perempuan menemui jalan buntu karena kekhawatiran cuti yang berakhir pemberhentian kerja.
Kondisi-kondisi tersebut yang membuat perempuan teralienasi dari tubuhnya karena kehilangan hak maternity-nya. Perusahaan dalam hal ini tidak memberikan fasilitas kesehatan yang layak dan terus mendorong pekerjanya untuk bekerja, tanpa memedulikan kondisi pekerja itu sendiri. Perusahaan terus berfokus untuk keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat pekerjanya sebagai “manusia”, khususnya terhadap perempuan. Perusahaan tidak menyadari bahkan abai, bahwa kondisi perempuan berbeda dengan laki-laki, yaitu berupa menstruasi, hamil, dan menyusui. Oleh sebab itu, perempuan perlu mendapatkan penanganan yang berbeda dengan pekerja laki-laki. Namun sangat disayangkan, kondisi tersebut tidak serta merta membuat perempuan mendapatkan fasilitas dari perusahan dan membuat buruh perempuan terus teropresi.
Menjawab pertanyaan sebelumnya mengenai tingkat kesempatan kerja perempuan yang rendah, memang tidak dapat dilihat langsung dari analisis kelas saja. Perlu dilihat kembali bahwa masyarakat kita hidup dalam sistem yang patriarkis. Angka partisipasi kerja perempuan yang rendah sangat erat kaitannya dengan tingginya partisipasi perempuan dalam ranah domestik (sebagai ibu rumah tangga). Meskipun “emansipasi” terus digembar-gemborkan pada masa kini, perempuan masih terbelenggu sekaligus terinternalisasi untuk menjadi “ibu yang baik”. Stereotipe ibu yang baik adalah perempuan yang mengurus anak dan keluarga. Tugas domestik tersebut dianggap sebagai bentuk abdi terhadap keluarga, sehingga pengorbanan untuk tidak bekerja di luar rumah dianggap “kodrat” dan “esensi ibu baik”.
Meskipun persentase ibu rumah tangga sangat tinggi, tidak jarang pula hadir perempuan yang bekerja di ranah publik. Perempuan pekerja ini juga tidak dapat dilihat secara gamblang dapat lepas dari tugas domestik. Mereka juga harus mengurus keluarga dan akhirnya mengalami multi burden (beban kerja ganda). Akibatnya, perempuan yang bekerja tidak dapat bekerja secara penuh dalam perusahaan dan membut dirinya tersubordinasi. Subordinasi yang dimaksud, yaitu ditempatkannya perempuan pada posisi tertentu saja yang dianggap “pekerjaan perempuan”. Perusahaan cenderung membatasi perempuan pada pekerjaan tertentu saja, seperti bendahara dan sekretaris. Jenis pekerjaan tersebut tentu memiliki penghasilan berbeda dengan jabatan lainnya.
Sama halnya dengan kasus di atas, perempuan lebih dominan bekerja sebagai buruh tani dan perikanan yang tingkat upah rata-ratanya terendah di Indonesia. Tentu saja kondisi tersebut berdampak pada tingginya kesenjangan upah perempuan terhadap laki-laki. Buruh perempuan terus mendapatkan upah rendah karena perusahaan menganggap perempuan hanya pencari nafkah sampingan. Selain itu, dengan adanya stereotipe “pekerjaan khas perempuan”, perempuan dianggap terampil dan mampu bekerja pada beberapa sektor saja, seperti industri tekstil, industri makanan, dan elektronika (Saptari & Holzner 459-460). Artinya, perempuan akan terus tersubordinasi karena stereotipe tersebut. Problema inilah yang membuat kelas perempuan mengalami opresi seperti yang diungkapkan oleh Arivia.
Melepaskan buruh perempuan dari bentuk opresi, nampaknya masukan Engels, Benston, dan comparable worth dapat menjadi alternatif. Sosialisasi pekerjaan domestik, mengutamakan kemandirian perempuan dalam hal ekonomi, dan penekanan “poin nilai” dalam pekerjaan dapat menjadi langkah strategis untuk melepaskan perempuan dari opresi. Solusi lain tentu perlu ditambahkan, seperti menuntut perusahaan untuk memberikan upah yang layak, asuransi dan jaminan kesehatan kepada buruh perempuan, fasilitas ruang laktasi, pemberian cuti menstruasi/haid, cuti melahirkan, fasilitas klinik dalam perusahaan, fasilitas air bersih, hingga fasilitas penitipan anak dalam perusahaan. Namun demikian, tentu saja hal tersebut tidak dapat serta merta melepaskan perempuan dari belenggu opresi. Poin yang perlu diingat, kita hidup dalam masyarakat yang patriarkis. Keluarga, masyarakat, dan negara perlu memberikan perlindungan dan dukungan terhadap perempuan agar dirinya mampu menjadi manusia yang utuh, terintegrasi, dan berbahagia sebagaimana yang diharapkan oleh feminisme Marx.
(Andi Nur Faizah)